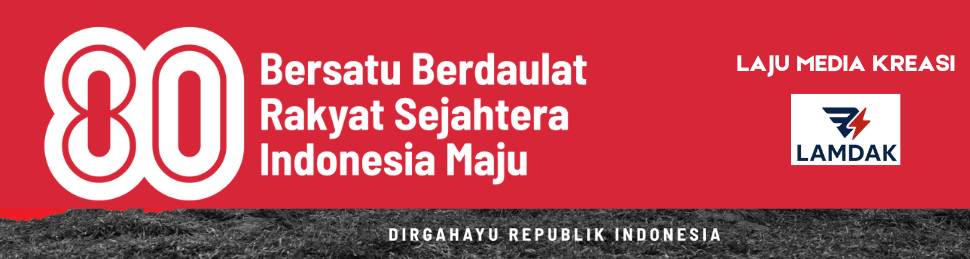Oleh: Ocky Anugrah Mahesa
Beberapa tahun terakhir, masyarakat Jawa Timur diresahkan oleh satu fenomena yang secara perlahan berubah dari tren hiburan menjadi persoalan sosial: Sound Horeg.
Istilah ini merujuk pada aktivitas iring-iringan kendaraan—biasanya truk yang telah dimodifikasi—yang membawa sound system berdaya besar, memutar musik secara ekstrem, dan menyita ruang-ruang publik untuk “berpesta”.
Fenomena ini bukan sekadar soal volume keras. Ini tentang bagaimana kebebasan berekspresi dimaknai secara keliru.
Tentang bagaimana ruang publik yang seharusnya menjadi tempat hidup bersama, justru menjadi milik sekelompok orang yang ingin memamerkan dentuman paling nyaring. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ini menunjukkan krisis kolektif dalam memahami batas antara hiburan dan perusakan sosial.
Tak heran jika gelombang penolakan dari warga di berbagai daerah di Jawa Timur kini kian menguat. Suara masyarakat dari desa-desa di Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, hingga Bangkalan bukan hanya suara resah—tetapi jeritan atas ruang hidup yang terganggu, waktu istirahat yang dirampas, dan keamanan sosial yang dipertaruhkan.
Fenomena ini bukan soal “anak muda butuh ruang berekspresi”. Ini soal bagaimana kita secara kolektif gagal mengatur relasi antara kebebasan individu dan kepentingan bersama.
Seiring dengan makin murah dan mudahnya akses terhadap perangkat audio berkekuatan besar, kita melihat munculnya budaya “unjuk gigi” baru dalam bentuk sound system war. Di sinilah Sound Horeg berkembang: bukan sekadar menyetel musik, tapi adu keras-kerasan volume, pamer modifikasi kendaraan, dan mobilisasi massa.
Dalam konteks budaya Jawa Timur, pesta rakyat selalu punya tempat. Namun, kita perlu membedakan antara budaya yang hidup dan budaya yang membahayakan.
Jaranan, kuda lumping, ludruk, dan reog—semua adalah seni pertunjukan rakyat yang lahir dari keteraturan sosial. Ada waktu, tempat, dan nilai edukatif yang dibangun.
Sementara Sound Horeg tidak demikian. Ia tidak lahir dari basis nilai, melainkan dari dorongan narsistik kolektif: ingin didengar, dilihat, dan viral.
Ini bukan akar budaya, melainkan dampak dari budaya popular yang tidak terkendali. Pesta suara di jalanan bukan bentuk perayaan tradisi, melainkan bentuk pelarian dari kebosanan yang tanpa penyaluran sehat.
Bahkan jika kita bicara hak berekspresi, kita tetap harus bicara konteks. Ekspresi yang merampas hak istirahat warga, yang menciptakan trauma suara bagi anak-anak, dan yang berpotensi menciptakan konflik sosial, bukanlah bentuk kebebasan. Itu bentuk kekerasan—secara akustik, sosial, dan psikologis.
Sound Horeg Melanggar Banyak Hal
Dari sisi regulasi, praktik Sound Horeg secara terang-terangan melanggar sejumlah norma hukum dan ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara tegas melarang penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jalan umum.
Kendaraan yang telah dimodifikasi tanpa standar keamanan jalan seharusnya tidak diperbolehkan berkeliaran.
Di sisi lain, polusi suara juga masuk ke dalam ranah yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Polusi suara adalah bentuk gangguan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia, baik secara fisik maupun mental.
Yang lebih problematik, praktik ini sering kali dilakukan tanpa izin resmi, tanpa koordinasi dengan aparat keamanan, dan seringkali di luar kendali pemerintah desa maupun kelurahan.
Ruang publik, yang seharusnya dijaga bersama, justru diubah menjadi zona anarki akustik yang menihilkan kepentingan warga lain.
Dalam praktiknya, Sound Horeg juga memperlihatkan bagaimana aparat negara cenderung bersikap permisif, bahkan pasif. Ketika ada konflik, barulah aparat hadir. Tetapi saat kegiatan itu mulai direncanakan, mulai mengganggu, atau bahkan mulai viral di media sosial, tak ada tindakan preventif yang serius.
Negara harus hadir bukan hanya sebagai pemadam kebakaran setelah keributan terjadi. Negara harus mampu menjadi regulator dan edukator dalam fenomena sosial yang berpotensi menciptakan konflik horizontal.
Menolak Dalam Diam
Gelombang penolakan terhadap Sound Horeg menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi tinggal diam. Di beberapa wilayah, kepala desa bersama tokoh masyarakat menginisiasi larangan konvoi sound system.
Di media sosial, warga mulai menyuarakan trauma dan kerugian yang mereka alami akibat aktivitas ini. Bahkan di beberapa tempat, warga melakukan swadaya patroli malam untuk mencegah iring-iringan horeg yang masuk ke wilayah mereka.
Namun perjuangan warga ini kerap berhadapan dengan masalah baru: kelompok pendukung Sound Horeg yang merasa “dikekang” dan balik mengintimidasi warga yang menolak.
Inilah yang menjadikan Sound Horeg bukan lagi sekadar budaya jalanan, tapi sudah berkembang menjadi ancaman sosial. Ketika ekspresi berubah menjadi tekanan terhadap orang lain, kita tidak lagi bicara soal “budaya”, tapi dominasi yang mengarah pada kekerasan sosial.
Yang menjadi ironi, sebagian pelaku Sound Horeg adalah pemuda usia produktif, yang seharusnya punya banyak potensi untuk diarahkan ke kegiatan positif.
Namun minimnya ruang publik yang inklusif, absennya pendidikan budaya, serta minimnya intervensi negara, membuat mereka lebih memilih jalan ekspresi yang keras—baik secara suara, maupun sikap.
Media sosial turut memperparah situasi. Banyak akun TikTok dan Instagram mempopulerkan video Sound Horeg sebagai hiburan. Dentuman musik disulap menjadi konten, ditambahi filter dramatis, dan dijadikan bahan “flexing” komunitas. Sayangnya, yang diangkat hanya sisi hebohnya, tanpa mengungkap dampak sosialnya.
Inilah bentuk kegagalan literasi media kita: kita membagikan apa yang heboh, tanpa menimbang apakah itu baik. Kita memviralkan suara keras, tanpa mendengar suara lirih dari warga yang terganggu.
Media seharusnya punya peran penting dalam menyeimbangkan narasi. Editorial seperti ini perlu menjadi suara penengah. Bahwa tidak semua ekspresi layak dibanggakan. Bahwa tidak semua tren patut dilestarikan. Bahwa keberanian bersuara juga harus dibarengi keberanian menegur yang keliru.
Jalan keluar tidak bisa hanya berupa pelarangan. Kita juga perlu menciptakan ruang-ruang alternatif yang sehat. Pemerintah daerah, komunitas seni, dan pemuda harus diajak duduk bersama untuk menyusun bentuk-bentuk ekspresi yang konstruktif. Festival musik lokal yang terjadwal, ruang komunitas seni terbuka, hingga platform digital berbasis karya bisa menjadi saluran positif.
Lebih dari itu, perlu dibangun kesadaran publik bahwa ruang hidup adalah milik bersama. Dan hak atas kenyamanan adalah hak yang sama pentingnya dengan hak berekspresi.
Kesadaran ini tidak bisa datang hanya dari larangan, tapi dari pendidikan budaya, literasi sosial, dan keteladanan aparat.
Beberapa desa di Jawa Timur sudah memulai. Mereka membuat kesepakatan bersama: larangan Sound Horeg, razia kendaraan modifikasi, dan sosialisasi ke pemuda setempat. Ini langkah yang patut didukung dan direplikasi.
Fenomena Sound Horeg adalah gejala. Ia menandakan adanya ruang kosong dalam kebijakan budaya, dalam pemberdayaan pemuda, dan dalam pengelolaan ruang publik.
Tapi bukan berarti harus membiarkannya tumbuh. Karena yang tumbuh liar, jika tidak dikendalikan, bisa menjadi duri yang melukai banyak orang.
Editorial ini tidak ditujukan untuk menyalahkan kelompok tertentu. Tapi untuk mengajak kita semua menyadari satu hal penting: bahwa kebebasan harus berdampingan dengan tanggung jawab. Bahwa ekspresi harus disertai etika. Dan bahwa ruang publik harus dijaga bersama.
Kita hidup dalam masyarakat yang saling terkait. Suara kita berdampak pada telinga orang lain. Perayaan kita berdampak pada ketenangan tetangga. Dentuman kita berdampak pada kehidupan sosial orang lain. Maka, sebelum kita menyalakan speaker, sebaiknya kita dengarkan dulu suara hati.
Karena dalam hidup bersama, yang paling dibutuhkan bukan suara paling keras, tetapi suara yang paling menghormati sesama.