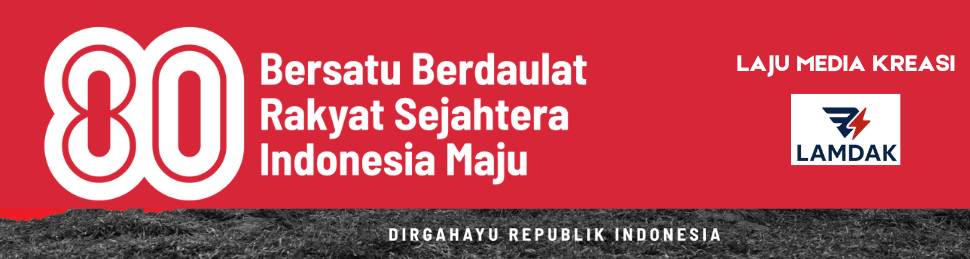Oleh: Ocky Anugrah Mahesa
Pajak adalah nafas negara. Begitu kata para ekonom dan pejabat yang berdiri di mimbar-mimbar resmi. Ia diibaratkan darah yang mengalir ke seluruh tubuh pemerintahan, memberi tenaga untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan semua infrastruktur yang tak mungkin lahir dari udara kosong.
Namun di negeri ini belakangan, nafas itu terasa sesak. Pajak yang semestinya menjadi urat nadi kesejahteraan, justru mulai terdengar seperti hembusan yang mengancam, menusuk ke segala arah, mencari mangsa di setiap celah kehidupan rakyat.
Negara butuh uang—itu yang kita pahami. Tapi kebutuhan itu kini diiringi hasrat yang kian rakus. Semua yang bergerak, semua yang berdenyut, semua yang bernafas, mulai masuk dalam daftar objek pajak.
Dari royalti musik yang mengalir dari denting gitar di kafe kecil, sampai kursi plastik yang menampung penonton di panggung kampung, semua ditakar, dihitung, ditagih. Bahkan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya, kini sudah ada mata orang pajak yang mengintipnya.
Mari kita lihat kasus royalti musik. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 lahir dengan dalih mulia: melindungi hak pencipta lagu, memastikan mereka mendapat bayaran yang layak dari karya yang menghidupi jiwa banyak orang.
Di atas kertas, kebijakan ini tentu bentuk keberpihakan. Tapi ketika sampai di lapangan, tarif yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terasa menampar usaha kecil.
Puluhan ribu rupiah per kursi per tahun untuk kafe dan bar; persentase tertentu dari harga tiket konser; ribuan rupiah per meter persegi untuk ruangan yang memutar musik, semuanya harus masuk dalam catatan pajak.
Logika ini mungkin adil untuk perusahaan besar, tapi menjadi palu godam bagi warung kopi pinggir jalan yang memutar lagu dari radio bututnya, demi bisa mendapat Rupiah dari orang-orang yang datang menyeduh ketenangan.
Ironinya, pemerintah justru menegaskan royalti ini bukan pajak, melainkan sebuah pertanggungjawaban pada hak cipta. Sebuah karya. Tetapi untuk membayarnya, pelaku usaha tetap harus merogoh kantong yang sama—kantong yang sudah robek oleh tarif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, retribusi daerah, bahkan pungutan informal yang tak tercatat di kas negara.
Dan jangan lupa, atas royalti yang diterima pencipta, masih ada Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto, atau 30% jika si penerima tak memiliki NPWP. Bayangkan: hasil jerih payah yang sudah dipotong oleh lembaga kolektif, masih diiris lagi oleh negara.
Alasan penerapan pajak ini adalah untuk menambah penerimaan negara dan demu pembangunan. Tetapi alasan ini kehilangan daya magisnya ketika rakyat melihat jalan rusak tak kunjung diperbaiki, rumah sakit masih penuh pasien yang tidur di lorong, dan sekolah negeri masih memungut iuran karena dana BOS tak cukup. Sesuatu yang sangat senjang.
Serikat buruh kini menjerit, pelaku usaha terjepit, sementara DPR dan pemerintah saling melempar tanggung jawab, seakan kenaikan tarif ini hanyalah angka yang mengapung di udara tanpa bobot sosial.
Di sisi lain, sistem administrasi pajak yang digadang-gadang menjadi modern justru memalukan di hari pertama peluncurannya. Per 1 Januari 2025, sistem elektronik pajak nasional diharapkan menjadi tonggak efisiensi.
Namun Yang terjadi: server tumbang, akses macet, data hilang, dokumen tak bisa diunduh. Pelaku usaha yang bergantung pada sistem ini untuk pelaporan dan pembayaran jadi kebingungan. Asosiasi Pengusaha Indonesia harus turun tangan menyuarakan protes.
Jawaban pemerintah? Permintaan maaf dan janji perbaikan. Namun di dunia bisnis, setiap hari keterlambatan adalah kerugian, dan kerugian itu tak pernah diganti.
Kita juga tidak bisa menutup mata pada fakta yang diungkap OECD: rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto adalah salah satu yang terendah di ASEAN. Artinya, bukan hanya tarif yang menjadi masalah, tapi efektivitas pemungutannya.
Alih-alih menutup kebocoran dan menertibkan yang besar-besar, pemerintah tampak memilih jalan pintas: memperluas objek pajak ke hal-hal yang remeh, yang nilainya kecil tetapi jumlahnya banyak.
Strategi ini ibarat memerah kambing kurus setiap hari, berharap susunya bertambah, padahal yang terjadi hanyalah hewan itu makin lemah. Bak sebuah pasar, negara seketika bak seorang Preman, yang kerap meminta jatah upeti pada para pedagang. Pengais nasib.
Di media sosial, suara rakyat bergaung. Ada yang mengeluh bahwa membayar pajak di negeri ini seperti membayar dua kali: sekali untuk negara, sekali lagi untuk kebutuhan yang seharusnya ditanggung negara tapi malah harus dibiayai sendiri. Jahat!
Bayar pajak jalan, tapi jalan berlubang; bayar pajak keamanan, tapi masih harus bayar satpam kompleks; bayar pajak pendidikan, tapi masih keluar biaya les karena kualitas sekolah tak merata.
Kritik yang muncul bukan berarti rakyat anti pajak. Sebaliknya, rakyat akan rela membayar jika percaya uang itu kembali dalam bentuk pelayanan publik yang nyata. Namun kepercayaan itu kini kian tipis.
Terlalu banyak kisah korupsi pajak yang terbongkar, terlalu sering terdengar berita pegawai pajak bergelimang harta tak wajar. Bagaimana mungkin rakyat percaya pada institusi yang kerap bocor dari dalam?
Fenomena pajak gila-gilaan ini juga berbahaya secara psikologis. Setiap kali pemerintah mengumumkan pajak baru atau kenaikan tarif, ada rasa takut yang menjalar.
Bukan takut pada kewajiban itu sendiri, tapi takut pada ketidakpastian: apakah nanti beban ini akan membuat usaha kecil gulung tikar? Apakah harga barang kebutuhan akan melambung? Apakah pekerjaan akan hilang karena perusahaan memotong biaya? Ketakutan ini perlahan mematikan semangat produktif, dan jika dibiarkan, akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.
Namun kritik ini tidak berhenti pada keluhan. Ada jalan yang bisa ditempuh jika pemerintah mau melihat pajak bukan semata mesin penghisap, melainkan instrumen pengelola kesejahteraan.
Pertama, terapkan prinsip progresivitas. Jangan hanya sekadar slogan di UU, tapi benar-benar menargetkan tarif tinggi pada kelompok super kaya dan korporasi raksasa, sambil memberi keringanan bagi UMKM, seniman kecil, dan pekerja kreatif yang berjuang sendirian.
Kedua, perbaiki sistem digital pajak dengan serius. Jangan meluncurkan sistem sebelum diuji ketahanan dan skalanya. Transparansi atas pengadaan dan operasional sistem ini juga wajib, agar publik tahu bahwa uang mereka tidak dihamburkan untuk proyek yang setengah matang.
Ketiga, kembalikan sebagian penerimaan pajak langsung ke rakyat dalam bentuk program yang terasa nyata: subsidi listrik untuk rumah tangga miskin, transportasi publik gratis di kota-kota besar, atau bantuan modal tanpa bunga untuk usaha mikro. Ini bukan sekadar “balas jasa”, tetapi cara membangun kepercayaan fiskal.
Keempat, hentikan praktik memperluas objek pajak ke ranah yang justru menghambat kreativitas dan inovasi. Royalti musik? Ya, lindungi hak cipta. Tapi jangan samakan tarif untuk konser stadion dan kafe kecil. Pajak digital? Ya, pungut dari raksasa teknologi global, bukan dari penjual keripik online yang omzetnya tak sampai seratus juta setahun.
Kelima, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Setiap skandal pajak yang melibatkan pejabat harus diselesaikan tuntas di pengadilan, dengan hukuman yang setimpal, tanpa kompromi politik. Sebab tidak ada reformasi pajak yang mungkin berjalan jika aparatnya sendiri tidak bersih.
Pajak, dalam pengertian paling murni, adalah perwujudan kontrak sosial: rakyat memberi sebagian penghasilannya untuk negara, negara memberi kembali rasa aman, kemakmuran, dan kesempatan yang setara. Namun kontrak ini rapuh, dan bisa runtuh jika salah satu pihak ingkar.
Saat ini, rakyat merasa negara yang lebih sering ingkar. Karena itu, reformasi pajak tidak cukup hanya dengan mengubah tarif dan sistem, tetapi juga mengubah sikap: dari memaksa menjadi mengajak, dari menagih menjadi melayani.
Kalau ini dilakukan, pajak tak lagi terdengar seperti ancaman. Ia akan menjadi simfoni yang dimainkan bersama: negara dan rakyat dalam harmoni, saling menghidupi, saling menguatkan. Dan barulah saat itu, kita bisa berkata bahwa pajak adalah nafas negara yang benar-benar memberi kehidupan, bukan malah berubah menjadi malaikat pencabut nyawa.